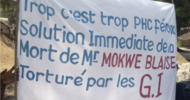Menyoal ‘Food Estate’ dan pemenuhan hak atas pangan
oleh Fuad Abdulgani dan Laksmi A. Savitri

Pandemi COVID-19 memperlihatkan sistem pangan negeri ini rentan krisis. Dampak pandemi terhadap sistem pangan bervariasi sejak ada beragam kondisi spesifik sistem pangan di penjuru Indonesia (McCharty dkk. 2021).
Dampak paling umum adalah distribusi pangan terganggu yang berimplikasi pada ketersediaan dan keterjangkauan pangan, tak hanya tingkat regional dan nasional, juga internasional (Ploeg 2020).
Di tengah potensi krisis pangan seperti peringatan dari organisasi pangan dunia (Food and Agriculture Organization) pada awal pandemi, Pemerintah Indonesia mengambil respon cepat dengan meluncurkan pryek peningkaran penyediaan pangan nasional (food estate). Proyek ini bagian dari proyek strategis nasional yang rilis melalui Peraturan Presiden No. 109 tahun 2020. Pada Maret lalu, food estate genap dua tahun.
Food estate atau komplek pangan skala-luas, yang punya rekam jejak kegagalan di masa-masa sebelumnya, kali ini muncul di tengah konteks lebih genting. Ia rilis ketika pandemi menunjukkan bahwa sistem pangan global dominan hari ini, yang terlalu bergantung pada rantai pasok komoditas, ternyata rentan saat menghadapi krisis (Ploeg 2020).
Di tengah gentingnya peringatan untuk menahan laju pemanasan global, desakan mentransformasi sistem pertanian dan pangan agar lebih berkelanjutan sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan dari aspek nutrisi, Indonesia tengah menghadapi beban ganda. Tengkes (stunting) karena asupan nutrisi minus masih menjadi masalah serius. Sementara penderita obesitas dan penyakit degeneratif lain cukup akut.
Dalam keadaan ini, apakah food estate pilihan tepat?
Pangan sebagai hak asasi manusia
Food estate mengacu pada cita-cita ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam analisis ekonom geografer Jeffrey Neilson, acuan ini menunjukkan, diskursus pangan dibangun berdasarkan imajinasi nation yang bersifat abstrak (Neilson 2017).
Acapkali praktik yang bertolak dari titik pandang ini alpa untuk melihat dimensi konkrit dari ketahanan pangan serta pemenuhan hak atas pangan secara lokal, pada tingkat individu, rumah tangga, dan komunitas (Hadiprayitno, 2010). Karena itu penting memeriksa bagaimana food estate berimplikasi pada kondisi pangan di tingkat lokal khusus pada komunitas petani yang dilibatkan.
Masalah pangan seringkali dibicarakan melalui lensa ketahanan dan kedaulatan pangan tetapi jarang dipahami sebagai sebuah hak asasi. Kandungan hak atas pangan memang termaktub dalam definisi kedaulatan pangan menurut UU Nomor 18/2012 tentang Pangan, namun tak ada penjelasan tentang hak atas pangan itu sendiri.
Disebutkan bahwa “kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.
Dengan demikian, menurut kerangka Undang-undang kebijakan pangan yang ditetapkan negara mestilah, pertama, menjamin hak atas pangan rakyat. Kedua, hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan sesuai dengan sumber daya lokalnya.
Konsepsi ini memberi kita rambu-rambu dalam mengamati peran negara. Sejauh mana negara dalam menentukan kebijakan pangan dapat menjamin terpenuhinya hak atas pangan dan hak masyarakat untuk menentukan sistem pangannya?
Pemahaman bahwa pangan adalah hak fundamental sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak asasi manusia lainnya sudah jadi kesepakatan global mengacu pada Poin 4 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Indonesia salah satu negara yang meratifikasi Kovenan itu. Kovenan mendefinisikan hak atas pangan layak (the right to adequate food) sebagai kondisi yang “terwujud ketika setiap laki-laki, perempuan, dan anak, secara individu atau bersama-sama di dalam komunitas, memiliki akses fisik dan ekonomi di sepanjang waktu atas pangan yang layak atau sarana untuk memperolehnya”.
Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan, Pemerintah Indonesia sebagai representasi dari negara dan pemangku kewajiban (duty bearer) seyogyanya merealisasikan hak itu.
Atas dasar ini, FoodFirst Information and Action Network (FIAN) Indonesia melakukan studi untuk memeriksa sejauh mana food estate dapat merealisasikan hak atas pangan.
Kebijakan industrikan pangan
Food estate dan kebijakan pembangunan pertanian yang menyokongnya merupakan modus pengaturan pertanian yang dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan tertentu. Food estate ini dirancang agar organisasi produksi yang dilaksanakan petani terintegrasi dengan rantai pasok agribisnis dan berorientasi ekspor. Pendekatan pembangunan pertanian berbasis komoditas.
Sebagai contoh, food estate di Kalimantan Tengah dengan komoditas padi dan ubi kayu. Sumatera Utara dengan hortikultura (kentang industri, bawang merah, dan bawang putih). Nusa Tenggara Timur dengan peternakan sapi pedaging.
Food estate maritim di Bali dengan komoditas udang vaname. Hal perlu digarisbawahi di sini, pelaksanaan food estate terjadi pada konteks geografis, agroekologis, sosio-kultural, serta pilihan komoditas pangan, organisasi produksi dan keterlibatan aktor-aktor yang berbeda-beda pada tiap lokasi.
Studi yang kami lakukan mengambil kasus food estate di desa Ria-ria, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Satu ciri food estate yang penting diperiksa berkenaan dengan desain pembangunan pertanian yang bertopang pada konsep korporasi petani-nya pemerintah dengan model closed loop (sistem tertutup) dengan inisiasi sektor swasta.
Korporasi petani merupakan rekayasa kelembagaan organisasi produksi petani untuk meningkatkan skala ekonomi melalui akumulasi modal. Kelembagaan petani ini dikaitkan dengan model closed loop hingga usaha tani akan terintegrasi dengan industri pangan yang dilakoni perusahaan-perusahaan agribisnis (swasta). Dengan asumsi korporasi atau kelembagaan petani akan menguat ketika terintegrasi dengan industri pangan.
Integrasi petani dengan agribisnis di food estate Sumatera Utara untuk produksi komoditas hortikultura yakni kentang industri, bawang merah, dan bawang putih. Komoditas ini dipilih karena bernilai ekonomis tinggi, dibutuhkan industri pangan, dan mampu melayani permintaan pasar global. Perlu digarisbawahi, tanaman komoditas ini relatif baru bagi petani Ria-ria.
Mekanisme kunci dari model closed loop yang berfungsi mengintegrasikan petani dengan agribisnis secara konkret mewujud dalam pola pertanian kontrak (contract farming).
Pertanian kontrak adalah model organisasi produksi yang mempertautkan petani kecil berbasis tenaga kerja rumah tangga dengan kontraktor. Dalam hal ini perusahaan agribisnis, melalui kontrak produksi-pemasaran yang disepakati di awal.
Kontraktor akan menginvestasikan input pertanian sesuai jenis yang dibutuhkan kepada petani, misal, benih, pupuk, dan pestisida. Petani wajib menjual hasil panen kepada kontraktor termasuk membayar kredit atas pinjaman input di muka di samping keuntungan bersih yang diterima.
Tak heran apabila dalam desain food estate Sumatera Utara, pemerintah sejak awal melibatkan dan mengalokasikan plot lahan bagi perusahaan agribisnis, seperti Indofood, Parna Raya, dan CalbeeWings, yang akan bertindak sebagai investor sekaligus pembeli (offtaker) hasil panen.
Mereka adalah perusahaan transnasional, dengan demikian kepentingan bisnis terletak pada rantai pasok komoditas di level internasional sekalipun mencakup pasar domestik.
Ketika petani memasuki relasi kontrak, maka akan terintegrasi secara vertikal dalam rantai komoditas pangan. Secara vertikal bermakna bahwa petani berkedudukan sebagai pemasok bahan mentah bagi industri pangan.
Dalam skema seperti ini, komoditas harus sesuai standar kelayakan industri. Konsekuensinya, budidaya tanaman petani tunduk pada preskripsi industri pangan.
Dalam analisis rantai komoditas pola demikian digolongkan sebagai buyer-driven (Gereffi, 1999). Produksi komoditas ditentukan oleh pembeli hasil panen, bukan oleh produsen langsung (petani). Hubungan seperti ini mengakibatkan hilangnya kendali petani dalam menentukan jenis tanaman yang akan ditanam, daya tawar terkait harga jual, dan makin pudarnya pengetahuan petani atas teknik budidaya tanaman-tanaman lokal.
Dalam perspektif studi agraria kritis, kondisi ini disebut sebagai ‘perampasan kuasa’ petani oleh korporasi (Borras dkk. 2012).
Dalam praktiknya, pola pertanian kontrak baru dilaksanakan pada musim tanam kedua. Pada musim tanam pertama usaha tani food estate dengan modal bantuan negara, disertai asistensi petugas lapang dari Kementerian Pertanian dan mahasiswa magang Polbangtan.
Seluruh modal persiapan aktivitas produksi, mulai dari pembukaan lahan, sertifikasi tanah, infrastruktur jalan dan pengairan, pelatihan kelompok tani, serta penyediaan input, sarana produksi pertanian, dan modal usaha tani, semua ditanggung APBN.
Dengan kata lain, pemerintah telah berperan dalam menyiapkan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan modal awal untuk episode pertanian kontrak antara petani dan sektor swasta.
Dengan melihat desain food estate di atas, apa yang tidak disebutkan dalam narasi ketahanan atau kedaulatan pangan sebetulnya adalah upaya mengindustrikan subsektor pertanian pangan yang selama ini ditopang oleh pertanian rumah tangga (smallholders).
Pertanyaannya, bagaimana proses industrialisasi ini berimplikasi terhadap hak atas pangan khusus produsen pangan itu sendiri yakni petani? (Bersambung)
*Penulis: Fuad Abdulgani adalah dosen di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung dan peneliti FIAN Indonesia. Laksmi A. Savitri adalah Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia